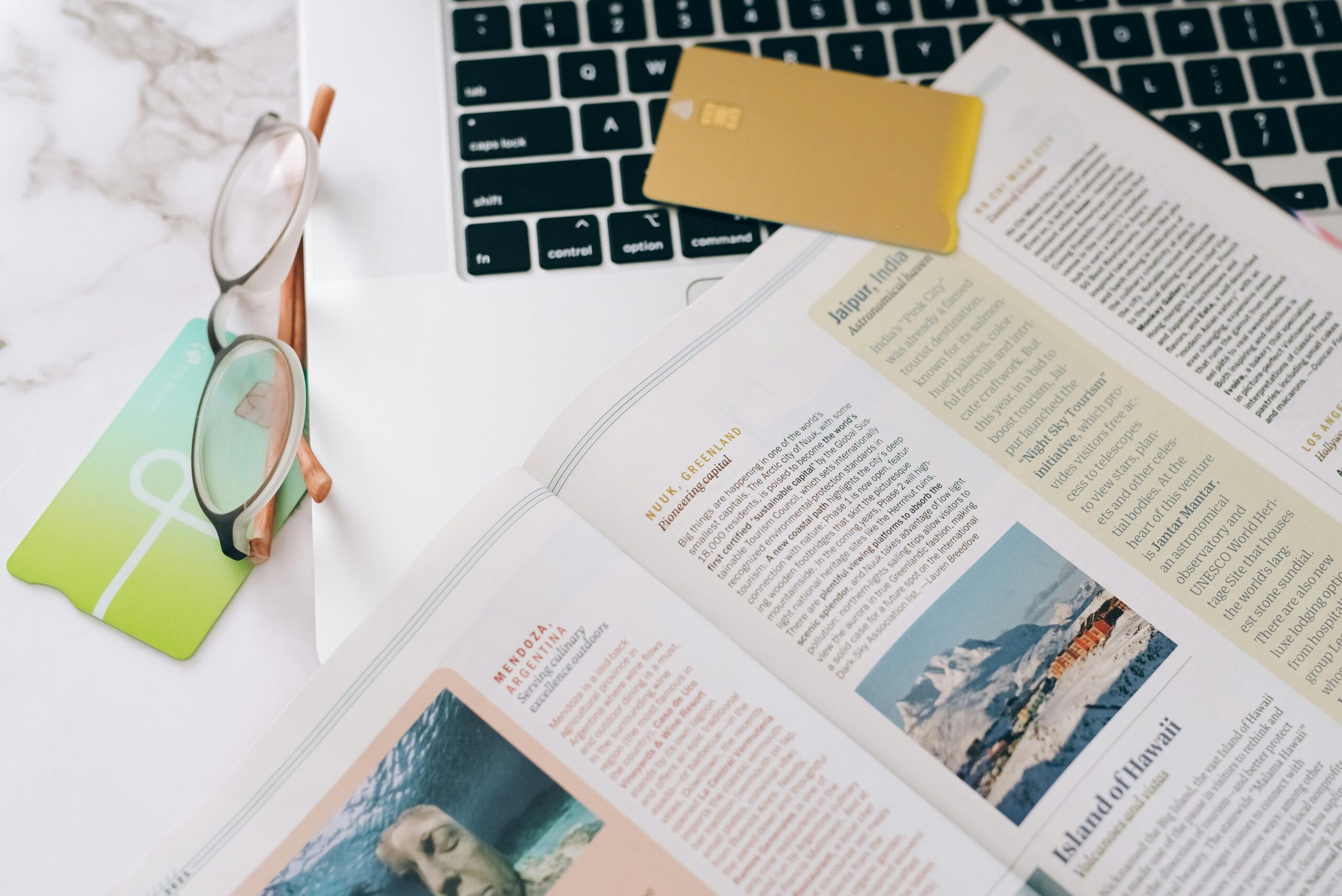Skala Likert adalah salah satu alat ukur yang paling populer dan banyak digunakan dalam penelitian sosial dan psikologi untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek atau pernyataan tertentu. Kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan kemampuannya menghasilkan data kuantitatif yang mudah dianalisis menjadikan skala Likert sebagai pilihan utama dalam berbagai bidang penelitian. Artikel ini akan membahas skala Likert secara komprehensif dengan lima pembahasan utama: pengertian dan definisi skala Likert, fungsi dan manfaat penggunaannya, jenis-jenis skala Likert, cara pengembangan dan penggunaan skala Likert, serta keunggulan dan keterbatasannya dalam penelitian ilmiah.
Baca Juga: Instrumen Pengukuran: Pengertian, Fungsi, Jenis, Proses Pengembangan, dan Pentingnya dalam Penelitian
Pengertian dan Definisi Skala Likert
Skala Likert adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang terkait dengan suatu objek penelitian. Skala ini dinamakan dari nama penemunya, Rensis Likert, seorang psikolog sosial Amerika yang mengembangkan metode ini pada tahun 1932.
Dalam prakteknya, skala Likert biasanya terdiri dari 5 sampai 7 pilihan jawaban yang menunjukkan derajat persetujuan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap jawaban diberi skor numerik, misalnya 1 untuk “sangat tidak setuju” hingga 5 untuk “sangat setuju”, sehingga hasilnya dapat diolah secara kuantitatif.
Skala Likert merupakan bagian dari skala ordinal, yang berarti data yang diperoleh menunjukkan urutan atau ranking, tetapi jarak antar kategori tidak selalu sama. Namun, banyak peneliti menganggap data skala Likert sebagai data interval untuk tujuan analisis statistik yang lebih kompleks.
Penggunaan skala Likert sangat populer dalam survei, kuisioner, dan instrumen pengukuran sikap karena kemudahan dalam perancangan dan interpretasi hasilnya. Selain itu, skala ini mampu mengakomodasi berbagai jenis variabel psikologis dan sosial yang sulit diukur secara langsung.
Skala Likert juga sering digunakan sebagai bagian dari instrumen pengukuran yang lebih luas, seperti dalam pengukuran kepuasan pelanggan, evaluasi kinerja, dan penelitian perilaku konsumen.
Fungsi dan Manfaat Penggunaan Skala Likert
Skala Likert memiliki fungsi utama sebagai alat pengukur sikap dan pendapat secara kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Fungsi ini sangat penting dalam penelitian sosial, psikologi, pemasaran, dan pendidikan yang bertujuan untuk mengukur persepsi, sikap, atau preferensi responden.
Pertama, skala Likert membantu peneliti mendapatkan data kuantitatif yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dibandingkan data kualitatif yang bersifat naratif.
Kedua, skala Likert memungkinkan pengukuran variabel yang sifatnya subjektif dan kompleks, seperti kepuasan, motivasi, kepercayaan, dan sikap sosial, dengan cara yang sistematis dan terstruktur.
Ketiga, penggunaan skala Likert memudahkan pengumpulan data dari responden yang jumlahnya besar secara efisien dan cepat. Dengan format yang standar dan mudah diisi, responden dapat memberikan jawaban tanpa kebingungan.
Keempat, data dari skala Likert memungkinkan analisis statistik yang beragam, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis inferensial seperti uji t, ANOVA, regresi, dan analisis faktor.
Kelima, skala Likert juga dapat digunakan untuk membandingkan kelompok responden atau untuk mengukur perubahan sikap dalam penelitian longitudinal atau evaluasi program.
Manfaat-manfaat ini membuat skala Likert sangat fleksibel dan relevan dalam berbagai jenis penelitian dan aplikasi praktis di bidang sosial dan bisnis.
Jenis-jenis Skala Likert
Skala Likert memiliki berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan konteks pengukuran. Berikut adalah beberapa jenis skala Likert yang umum digunakan:
- Skala Likert 5 Poin: Merupakan bentuk yang paling umum, dengan pilihan jawaban dari “Sangat Tidak Setuju” (1) hingga “Sangat Setuju” (5). Model ini cukup sederhana dan mudah dipahami responden.
- Skala Likert 7 Poin: Menambah tingkat granularitas dengan dua pilihan tambahan di tengah, misalnya “Tidak Setuju” (2), “Netral” (4), dan “Setuju” (6), sehingga memberikan variasi jawaban yang lebih halus.
- Skala Likert 4 Poin: Digunakan untuk memaksa responden memilih tanpa opsi netral, seperti dari “Tidak Setuju” (1) sampai “Sangat Setuju” (4), sehingga mendorong keputusan yang lebih pasti.
- Skala Likert dengan Label Khusus: Kadang-kadang, label pada skala bisa disesuaikan dengan konteks, misalnya mengganti “Setuju” dengan “Sangat Puas” dalam survei kepuasan pelanggan.
- Skala Likert Berbeda untuk Pengukuran Frekuensi atau Intensitas: Selain mengukur sikap, skala ini juga bisa dimodifikasi untuk mengukur frekuensi kejadian (misalnya dari “Tidak Pernah” sampai “Selalu”) atau intensitas perasaan (dari “Sangat Lemah” sampai “Sangat Kuat”).
Jenis-jenis skala Likert ini memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi instrumen pengukuran sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik responden.
Cara Pengembangan dan Penggunaan Skala Likert
Pengembangan skala Likert harus dilakukan dengan cermat agar hasil pengukuran valid dan reliabel. Proses pengembangan melibatkan beberapa langkah berikut:
Pertama, menentukan konstruk atau variabel yang akan diukur, seperti sikap terhadap suatu produk atau persepsi terhadap kebijakan tertentu. Penentuan variabel harus didasarkan pada tinjauan literatur dan tujuan penelitian.
Kedua, merancang pernyataan yang jelas dan relevan yang dapat menggambarkan variabel tersebut. Pernyataan harus singkat, tidak ambigu, dan mudah dipahami responden.
Ketiga, menentukan jumlah poin pada skala, apakah 5, 7, atau jumlah lain, dengan mempertimbangkan tingkat detail data yang dibutuhkan dan kemampuan responden.
Keempat, memberikan instruksi yang jelas kepada responden tentang cara mengisi skala, sehingga mereka memahami arti setiap pilihan jawaban.
Kelima, melakukan uji coba (pilot test) terhadap instrumen untuk mengidentifikasi masalah dalam pernyataan atau skala dan melakukan revisi jika diperlukan.
Setelah instrumen siap, dalam proses pengumpulan data, peneliti harus memastikan kondisi yang nyaman bagi responden agar mereka dapat memberikan jawaban yang jujur dan akurat.
Poin Penting dalam Penggunaan Skala Likert:\
- Gunakan bahasa yang sederhana dan netral dalam pernyataan.
- Hindari pernyataan ganda yang dapat membingungkan responden.
- Sertakan pernyataan positif dan negatif untuk mengurangi bias.
- Pastikan instrumen tidak terlalu panjang agar tidak membebani responden.
- Lakukan analisis statistik untuk menguji validitas dan reliabilitas skala.
Keunggulan dan Keterbatasan Skala Likert
Skala Likert memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan utama dalam banyak penelitian. Pertama, skala ini mudah dibuat dan digunakan, serta tidak memerlukan waktu lama bagi responden untuk mengisinya.
Kedua, skala Likert memberikan data kuantitatif yang mudah dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid.
Ketiga, skala ini mampu mengukur variabel yang bersifat subjektif dan kompleks dengan cara yang sederhana dan terstruktur.
Keempat, skala Likert fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai konteks dan jenis variabel yang berbeda.
Namun, skala Likert juga memiliki keterbatasan. Pertama, adanya kecenderungan responden memilih jawaban tengah (netral) atau jawaban sosial yang dianggap lebih diterima (social desirability bias).
Kedua, data yang diperoleh bersifat ordinal sehingga terkadang sulit untuk dianalisis dengan metode statistik yang mensyaratkan data interval.
Ketiga, perbedaan interpretasi antara responden terhadap tiap poin skala bisa menyebabkan variasi hasil yang tidak diinginkan.
Keempat, instrumen yang buruk dirancang dapat menyebabkan bias atau kesalahan pengukuran.
Meskipun demikian, dengan desain dan pengelolaan yang baik, keterbatasan ini dapat diminimalkan dan skala Likert tetap menjadi alat ukur yang sangat berguna dalam penelitian.
Baca Juga: validitas Instrumen Penelitian Teori, Jenis, dan Cara Pengujian
Kesimpulan
Skala Likert adalah alat ukur yang sangat populer dan efektif untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dengan cara yang sistematis dan kuantitatif. Kemudahan penggunaannya dan kemampuan untuk menghasilkan data yang mudah dianalisis menjadikannya pilihan utama di berbagai bidang penelitian sosial, psikologi, pemasaran, dan pendidikan. Fungsi utama skala Likert adalah sebagai media pengukuran sikap secara kuantitatif yang memungkinkan evaluasi, perbandingan, dan pengujian hipotesis secara objektif. Variasi jenis skala Likert memungkinkan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Pengembangan skala Likert harus melalui proses yang cermat mulai dari perumusan pernyataan, penentuan poin skala, hingga uji coba untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen. Penggunaan skala Likert juga harus memperhatikan desain dan teknik analisis yang tepat agar hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika Anda memiliki keraguan dalam pembuatan skripsi pengungsi politik global Anda dapat menghubungi Akademia untuk konsultasi mengenai skripsi pengaruh terorisme global yang telah Anda buat dan dapatkan saran terbaik dari mentor profesional yang kredibel dibidangnya.